Penulis : Oke Hariansyah , Universitas Pamulang
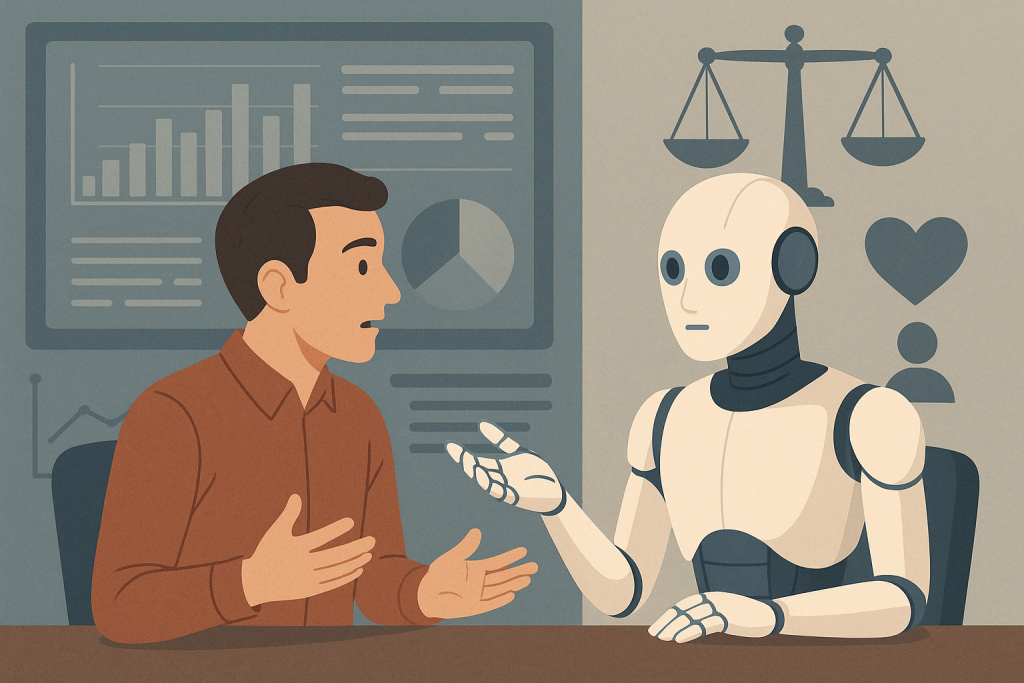
Di era kecanggihan teknologi saat ini, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai proses pengambilan keputusan. Mulai dari dunia medis, keuangan, pendidikan, hingga manajemen krisis, AI digunakan untuk menyaring data, memprediksi risiko, hingga memberikan rekomendasi berdasarkan pola dan statistik. Tidak dapat dipungkiri, efisiensi dan kecepatan yang ditawarkan AI memberikan lompatan besar dalam cara manusia mengambil keputusan yang kompleks.
Namun, semakin jauh teknologi mengambil alih, semakin perlu kita bertanya: apakah setiap keputusan bisa — dan seharusnya — diserahkan kepada mesin? Meskipun AI dapat mengolah jutaan data dalam hitungan detik, ia tidak memiliki intuisi, empati, atau pemahaman konteks sosial dan moral yang sering kali dibutuhkan dalam pengambilan keputusan nyata. Keputusan yang berkaitan dengan keadilan, rasa aman, dan nilai-nilai hidup tidak dapat hanya diukur dengan angka, melainkan juga oleh hati nurani.
Salah satu kekhawatiran utama adalah ilusi netralitas dalam AI. Banyak yang menganggap bahwa karena AI “berbasis data”, maka ia objektif. Padahal, data yang digunakan bisa saja berasal dari sistem yang sudah bias sejak awal. Jika tidak diawasi, AI dapat memperkuat ketimpangan, mengecualikan kelompok rentan, atau menormalisasi diskriminasi atas nama efisiensi. Di sinilah pentingnya manusia sebagai pengendali utama dari sistem yang diciptakannya.
AI adalah alat bantu — bukan penentu akhir. Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh teknologi, manusia tetap harus berada di pusat proses pengambilan keputusan. Bukan karena manusia selalu lebih tepat, tetapi karena hanya manusia yang mampu memadukan logika, etika, dan empati. AI yang bijak adalah AI yang dikendalikan oleh manusia yang bijaksana.